
Oleh: M. Husni Fahruddin Al Ayub, A.Md, S.Hut, SH, MH CLA - Ketua Tim Pemenangan AnNuR
Ketika lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, saya ingat pesan paman saya. Beliau adalah KH. Sabri Ismail, pimpinan Pondok Pesantren Karya Pembangunan Ribathul Khail Tenggarong, Kutai Kartanegara—semoga Allah SWT merahmati almarhum. Beliau berpesan agar saya menerapkan ilmu di ponpes sebagai guru biologi dan teknologi informasi.
Ya, saya adalah guru. Saya tahu benar rasa dan asa sebagai guru. Di ponpes, saya di panggil ustaz, walaupun saya bukan guru agama. Mahfum di ponpes, guru dipanggil ustaz.
Sebagai guru di sana, saya harus mengubah kebiasaan ketika menimba ilmu di institusi pendidikan umum. Saya harus siap bangun 3/4 malam untuk bersama-sama santri ke masjid, melaksanakan salat Tahajud dan tafakur, dilanjutkan salat subuh berjamaah, lalu mengikuti kutbah subuh.
Kegiatan sekolah di ponpes sendiri dimulai pukul 07.15 Wita. Saya harus bersiap untuk mengajar dengan instrumen laboratorium biologi dan komputer yang sangat minim. Namun saya tetap mencoba untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman terhadap kedua mata pelajaran tersebut.
Tuntas mengajar sekira pukul 14.00 Wita, saya lanjutkan dengan kuliah lanjutan dan aktif berorganisasi—kebiasaan yang saya geluti sejak mahasiswa. Jelang Magrib, saya baru kembali ke ponpes, salat berjamaah bersama santri, dan dilanjutkan dengan Talimul Quran.
Ya, kadang, saya mencoba mengajar baca Quran untuk para santri baru. Tentu harus santri baru, karena saya bukan ahlinya Nahwu Shorof. Jelang Isya, saya bersiap untuk salat berjamaah dan mendengarkan ceramah—sekaligus petuah—dari asatidz sepuh. Selesai itu, menulis artikel, bertemu sesama aktivis, menyusun gerakan organisasi, dan sedikit bisnis kecil-kecilan membantu teman pengusaha sampai malam hari.
Saya tahu bagaimana rasanya menjadi seorang guru dengan honor yang diterima saat itu. Hanya Rp 250 ribu. Tentu saja sangat tidak mencukupi. Wajar saja, banyak teman sejawat saya yang lain mencari alternatif pekerjaan untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari.
Ada yang menjadi guru honor di sekolah lain setelah selesai mengajar di Ponpes Karya Pembangunan Ribathul Khail.
Maklum, ustaz dan ustazah di ponpes terkenal ahlinya dibidang ke-Islama-an. Selain itu, mereka juga mengajar mengaji di rumah-rumah masyarakat, berjualan di pasar, membuka warung, bahkan ada yang menjadi ojek dan tukang bangunan di sela-sela jam pelajaran kosong.
Kebijakan pemerintah yang memberikan insentif sedikit berpengaruh untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup, namun persyaratan untuk mendapatkan insentif ini sangatlah ketat. Sehingga, bila mendapatkan insentif, otomatis pekerjaan sampingan tidak bisa dilakukan lagi. Bila dihitung-hitung, ternyata insentif tidak lebih banyak dari pendapatan pekerjaan sampingan para guru. Belum lagi sering kali insentif terlambat dicairkan. Inilah yang menjadi fenomena tersendiri bagi para guru.
Guru mengajar lebih dari satu mata pelajaran? Ah, itu biasa. Masih sangat banyak ditemukan di Kalimantan Timur.
Ada guru yang mengajar dan menjadi wali kelas di beberapa kelas sekaligus, itu juga biasa, masih banyak ditemukan. Banyaknya guru honorer di sekolah merupakan fenomena yang kerap terjadi. Sebab secara faktual, kuantitas guru memang kurang dibandingkan kuantitas murid.
Ilmu guru tidak semakin meningkat, bahkan bisa dikatakan tidak berbanding lurus dengan keilmuan siswa di setiap zaman yang dibimbingnya. Sekali lagi, itu lumrah.
Sebab bagaimana sulitnya guru memenuhi kebutuhan hidup, sehingga tidak mungkin untuk belajar dulu sebelum mengajar. Tidak mungkin mengikuti perkembangan teknologi dengan gaji yang minim. Tidak mungkin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, jika beasiswa tidak jelas peruntukannya. Belum lagi, ketika yang mengurusi para guru di kementerian dan dinas pendidikan dihuni oleh para pejabat yang bukan berasal dari tenaga pendidik. Makin kacau dunia pendidikan!
Anehnya lagi, amanat Undang-Undang yang mewajibkan setiap anggaran pendapatan dan belanja—baik di pusat dan daerah—untuk mengalokasikan sebesar 20 persen bagi dunia pendidikan, nampaknya hanya dijadikan formalitas semata.
Saya paham betul kehidupan seorang guru, sebab saya adalah guru. Bagaimana mentalnya, psikologinya, harapan hidupnya, cita dan asanya, masa depannya, suka dukanya, dimana letak kebahagiaannya. Apa itu sukses bagi dirinya? Guru tidak meminta lebih. Guru hanya ingin melihat anak didiknya memiliki kualitas bekal diri yang mumpuni untuk mengarungi bahtera kehidupan. Namun untuk menciptakan anak didik yang berkualitas, maka yang mendidik pun tentu saja harus diciptakan berkualitas. Bagaimana menciptakan guru dan murid berkualitas? Itu ada di dalam benak seorang guru yang sampai saat ini belum bisa diejawantahkan oleh pengusa negeri.
Siang tadi, saya sempat tersentak di tengah silaturahmi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Ternyata, telah lama saya tidak menikmati rasa bahagia menjadi seorang guru. Sekarang saya seorang praktisi hukum dan bergelut juga di zona politik praktis. Tapi kerinduan untuk berbicara, mengajar, mendidik, membina, memberikan penjelasan, serta pemahaman kepada anak didik kembali memenuhi ruang dada. Ya, saya tersentak. Di momentum itu, saya ingin sekali mengatakan ini kepada setiap orang; jangan lupakan guru. Jika negara ini ingin menjadi bangsa yang besar, maka angkatlah derajat para guru dan institusi pendidikan.
Lima belas tahun lalu dan hari ini, saya kembali mengingat pesan paman, KH. Sabri Ismail; ìSebesar apapun nantinya awak (kamu, Red.), walau awak bergelar (titel pendidikan, Red.) setinggi langit, awak tetap kemenakanku (keponakanku, Red.), dan kuminta awak untuk tetap kembali ke ponpes yang tercinta ini, mengabdi pada negara dan bangsa melalui ponpes ini.î (*)




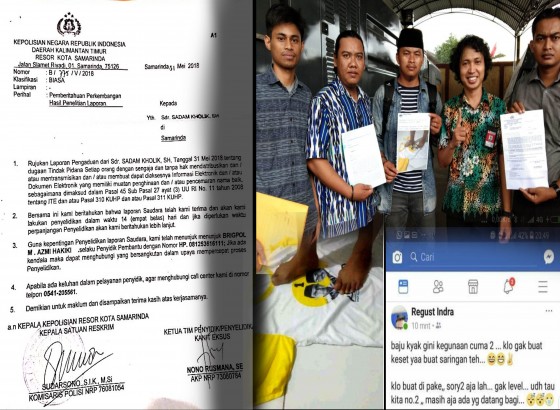

Masukkan alamat email untuk mendapatkan informasi terbaru